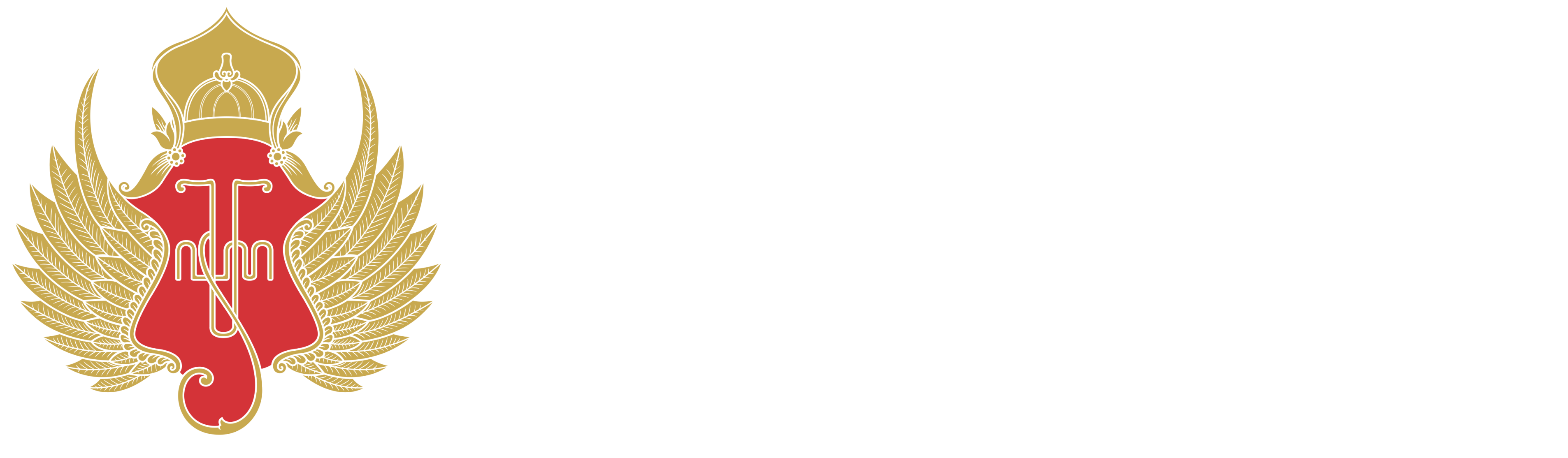Dilahirkan dengan nama Gusti Raden Mas (GRM) Mustojo pada tanggal 10 Agustus 1821, beliau adalah putera dari Sri Sultan Hamengku Buwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kencono. Pada tahun 1839 ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi beliau mendapat pangkat Letnan Kolonel dari pemerintah Hindia Belanda. Kelak pangkat beliau naik menjadi Kolonel pada tahun 1847.
Sri Sultan Hamengku Buwono V wafat dalam kondisi tidak meninggalkan putera. Selang 13 hari kemudian, baru sang permaisuri -GKR Sekar Kedaton, melahirkan seorang putera yang diberi nama GRM. Timur Muhammad yang bergelar Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryaning Ngalaga ketika sudah dewasa. Mengatasi kondisi tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang dinobatkan pada tanggal 5 Juli 1855.
Menginjak usia 27 tahun, beliau menikah dengan GKR Kencono yang merupakan puteri dari Susuhunan Paku Buwono VIII dari Surakarta. Sebagai permaisuri Sultan Hamengku Buwono VI, Ratu Kencono bergelar GKR Hamengku Buwono. Pernikahan tersebut menjadi sejarah terjalinnya kembali hubungan baik di antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang sejak Perjanjian Giyanti sering terjadi ketegangan. Hubungan baik dengan kerajaan lain juga semakin terjalin setelah Sri Sultan Hamengku Buwono VI menikahi puteri dari Kerajaan Brunei.
Pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VI pada dasarnya melanjutkan model yang dijalankan oleh kakaknya, perang pasif. Hal ini cukup berbeda dengan sikap beliau sebelum naik tahta, dimana beliau cukup keras menentang sikap sang kakak. Perubahan sikap ini kiranya yang menimbulkan kekecewaan dan akhirnya memunculkan gejolak di Kasultanan. Adalah kebetulan beliau didampingi oleh Patih Danurejo V yang terkenal pandai dalam hal siasat, sehingga banyak masalah pelik dapat terselesaikan.
Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI, terjadi bencana alam yang memilukan. Gempa dengan kekuatan dahsyat menggoncang bumi Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1867. Tercatat gempa mengakibatkan sekitar 500 korban jiwa. Selain itu, gempa juga memporak porandakan 327 bangunan termasuk bangunan keraton. Tugu Golog Giling (sekarang Tugu Jogja) yang tadinya menjulang 25 meter, rusak parah. Demikian juga bangunan Tamansari mengalami kerusakan hebat. Hal yang sama melanda Mesjid Gedhe dan Loji Kecil (sekarang istana kepresidenan Gedung Agung).
Perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut membutuhkan waktu lama. Bahkan, Tugu Golong Gilig baru selesai proses pembangunan ulangnya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII. International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology mencatat gempa waktu itu memiliki kekuatan sebesar 6,8 SR.
Sedemikian traumatisnya peristiwa tersebut sehingga Sri Sultan Hamengku Buwono VI meminta agar peristiwa tersebut tidak usah diingat-ingat dan meyakinkan penduduk bahwa peristiwa seperti itu hanya akan terjadi sekali, tidak akan terulang lagi. Itulah mengapa catatan mengenai gempa ini hanya terserak dalam ingatan-ingatan, tidak ada catatan atasnya secara rinci di karya-karya pujangga keraton.
Pada tanggal 20 Juli 1877 (9 Rejeb 1806 TJ), ketika beliau menginjak usia 56 tahun, Sri Sultan Hamengku Buwono VI tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Besiyaran, Pajimatan Imogiri. Sebulan berikutnya, tepatnya tanggal 13 Agustus 1877, putra beliau Raden Mas Murtejo naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
Peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono VI
Sri Sultan Hamengku Buwono VI meninggalkan dua buah karya seni tari, yaitu tari Bedhaya Babar Layar dan Srimpi Endra Wasesa.
Di masa beliau pula, dipesan kereta Kyai Wimono Putro yang nantinya menjadi kereta yang dipergunakan ketika diadakan upacara pelantikan putra mahkota menjadi sultan. Adapun kereta kebesaraan beliau sendiri, yang nantinya dipakai hingga sekarang, adalah Kyai Kanjeng Garudho Yakso.