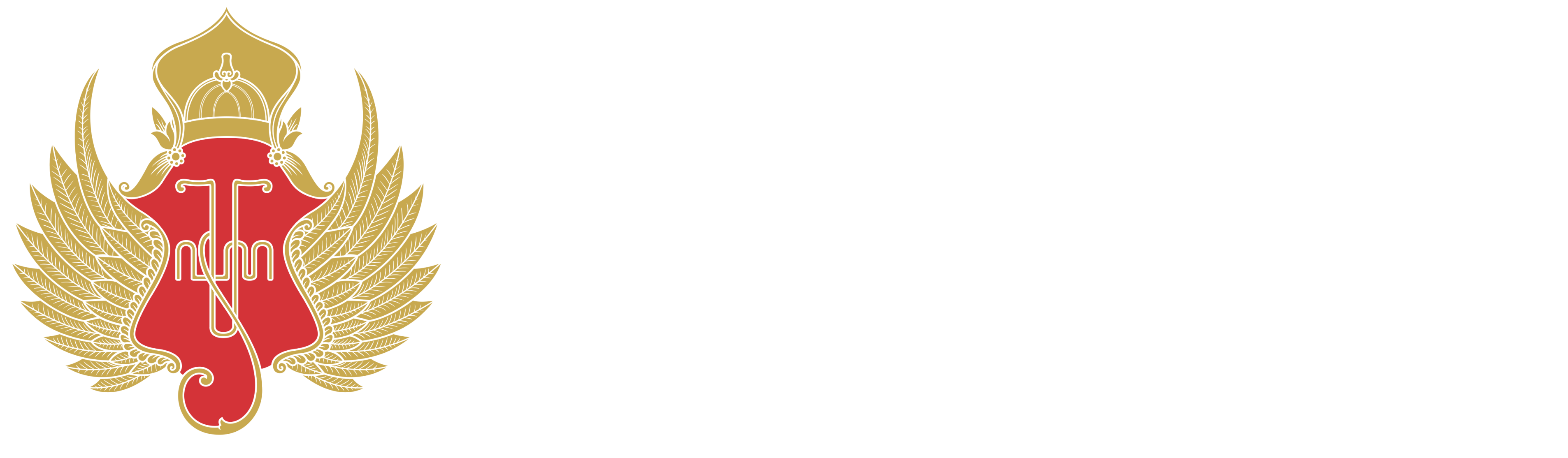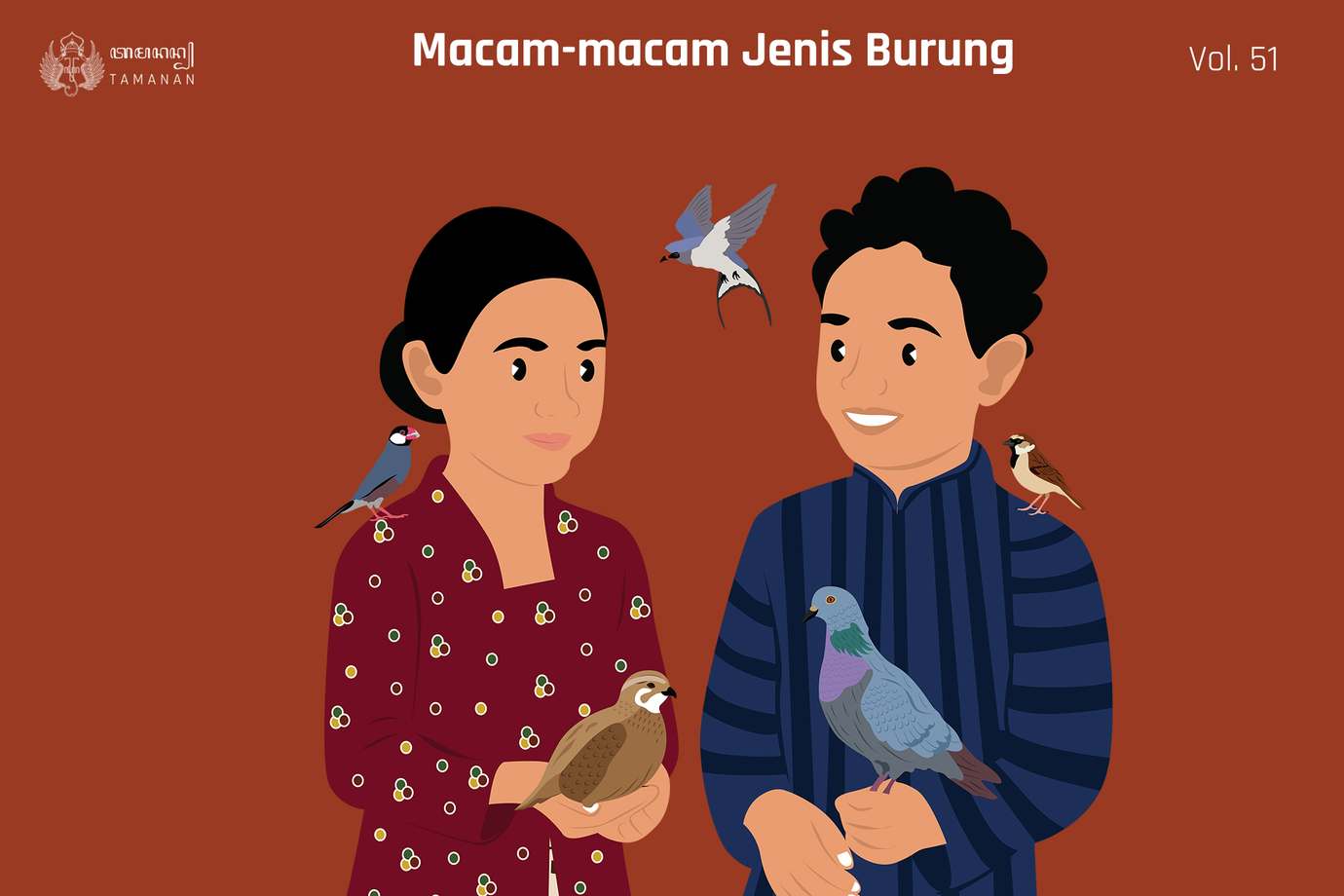Takhta Yogyakarta dan Gelombang Zaman
- 06-11-2017

Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Presiden Soekarno di Siti Hinggil. Foto koleksi BPAD DIY
Kesultanan Yogyakarta telah mengarungi pasang surut gelombang zaman selama lebih dari dua setengah abad. Yogyakarta lahir di masa kekuasaan VOC. Jatuh bangun dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, Perancis, dan Inggris. Bertahan di masa pendudukan Jepang. Bergabung sekaligus menyelamatkan Republik Indonesia. Kemampuan Kesultanan Yogyakarta untuk senantiasa menjaga kedaulatan politiknya sekaligus mengembangkan kebudayaan Jawa tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para Sultan yang bertakhta.
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792)
Setelah menghadapi peperangan panjang yang tak berkesudahan, VOC dan Pangeran Mangkubumi akhirnya sepakat untuk berunding. Perundingan ini menghasilkan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Ditandatangani pada 13 Februari 1755, perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Selain ahli strategi dan panglima perang yang cakap, Sri Sultan Hamengku Buwono I juga dikenang sebagai seorang arsitek yang visioner. Kota dan Keraton Yogyakarta dirancang serta dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional sebuah ibukota kesultanan, namun juga memperhatikan aspek-aspek filosofis dan spiritual. Kedua matra tersebut masih dapat dilihat dan rasakan hingga kini.
Sebagai peletak dasar-dasar kebudayaan Mataram Gaya Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono I telah merumuskan serangkaian tata nilai yang menjadi pedoman bagi para penerusnya dalam membangun dan mempertahankan eksistensi Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1810; 1811-1812; 1826-1828)
Sejak masih menjadi putra mahkota, Sri Sultan Hamengku Buwono II sudah menampakkan sikap bermusuhan dengan VOC. Sikap ini terlihat pertama kali pada tahun 1785 ketika dalam waktu singkat Keraton Yogyakarta telah dikelilingi oleh benteng yang cukup kuat. Benteng keraton yang dikenal sekarang ini merupakan inisiatif dari sang putra mahkota.
Saat itu VOC sedang terpuruk. Pada 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dialihkan kepada pemerintah Belanda. Namun seiring dengan rangkaian perang di Eropa yang dipicu Revolusi Perancis pada tahun 1789, kekuasaan atas wilayah kolonial di Jawa pun mengalami imbas. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda diambil alih Perancis yang sedang menguasai Belanda. Tidak berapa lama, Hindia-Belanda jatuh ke Inggris yang sedang berperang melawan Perancis. Tekanan kolonial pada Keraton Yogyakarta pun semakin meningkat.
Perseteruan ini memuncak pada serangan pasukan Inggris pada 21 Juni 1812 yang berhasil menembus pertahanan keraton. Kekalahan tersebut diiringi oleh penjarahan besar-besaran atas keraton, baik harta maupun naskah-naskah berharga.
Kesultanan Yogyakarta masih bertahan dengan diangkatnya putra mahkota sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono III. Namun Yogyakarta mengalami kemunduran baik dari segi luas wilayah, kedaulatan politik, kekuatan militer, maupun kemampuan ekonomi.
Sri Sultan Hamengku Buwono III (1810-1811; 1812-1814)
Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono III tidak berlangsung lama. Hanya 29 bulan setelah memerintah, beliau wafat. Dalam masa yang begitu singkat, beliau harus menata keadaan keraton yang kacau balau pasca kekalahan, serta mempertahankan kedaulatan yang masih tersisa di istananya.
Sri Sultan Hamengku Buwono IV (1814 – 1823)
Sri Sultan Hamengku Buwono IV dinobatkan saat masih berumur 10 tahun. Dalam usianya yang masih begitu muda, Sri Sultan Hamengku Buwono IV didampingi oleh suatu dewan wali. Beliau baru mulai memerintah penuh setelah berumur 16 tahun pada tahun 1820.
Pada masa pemerintahannya, kekuasaan pemerintah kolonial di Jawa beralih dari Inggris kembali ke Belanda. Seperti mendiang ayahandanya, beliau juga memerintah dalam kurun waktu yang cukup singkat. Beliau wafat pada usia 19 tahun dengan meninggalkan pewaris tahta yang masih sangat belia.
Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1826; 1828-1855)
Saat dinobatkan menggantikan ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono V baru berusia 3 tahun. Dewan perwalian pun kembali dibentuk untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan sampai sultan telah cukup umur. Pada masa ini terjadi peperangan terbesar yang pernah dialami pemerintah kolonial. Perang yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830) ini terjadi merupakan perlawanan Pangeran Diponegoro, salah satu wali sultan, terhadap kekuasaan kolonial yang sewenang-wenang.
Perang Jawa berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Pemerintah kolonial yang trauma kemudian memangkas kemampuan militer Yogyakarta.
Keadaan damai setelah perang serta tekanan pada militer dan politik yang kuat membuat Sri Sultan Hamengku Buwono V mencurahkan pemikiran pada mengembangkan seni budaya. Pada masa inilah budaya Jawa mengalami perkembangan pesat.
Sri Sultan Hamengku Buwono V mengembangkan musik yang memadukan gamelan Jawa dengan alat musik Eropa seperti terompet, trombon, suling, dan tambur. Musik ini disebut sebagai Gendhing Kapang-Kapang. Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono V juga menciptakan Bedaya Kakung, tarian Bedaya yang dibawakan oleh penari laki-laki.
Selain mengembangkan seni musik dan seni tari, Sri Sultan Hamengku Buwono V juga mengembangkan seni kesusastraan. Salah satu karya besar yang dihasilkan oleh beliau adalah Serat Puji. Serat Puji merupakan karya sastra berisi ajaran-ajaran moral bagi yang berkuasa.
Sri Sultan Hamengku Buwono VI (1855 – 1877)
Pada tahun 1867, Yogyakarta dilanda gempa besar. Gempa ini menimbulkan banyak kerusakan, termasuk bangunan-bangunan keraton. Sumber daya keraton dan perhatian Sri Sultan Hamengku Buwono VI banyak terserap dalam proses pemulihan ini. Proses ini bahkan belum selesai ketika beliau wafat pada tahun 1877.
Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877 – 1921)
Sri Sultan Hamengku Buwono VII bertakhta saat liberalisasi ekonomi mulai diterapkan untuk menggantikan sistem tanam paksa (1830-1870). Keadaan ini dimanfaatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan mendirikan unit usaha berupa pabrik-pabrik gula dan vanili. Keuntungan yang didapat oleh beliau tidak hanya cukup untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa, namun juga mampu mengisi perbendaharaan kesultanan. Bahkan, Sri Sultan Hamengku Buwono VII juga dikenal sebagai Sultan Sugih (Sultan nan Kaya).
Selain itu, seiring dengan meningkatnya perhatian pada bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengku Buwono VII mendirikan sekolah di Bangsal Srimanganti Keraton Yogyakarta. Beliau juga mengeluarkan kebijakan bahwa setiap pejabat keraton yang akan menggantikan jabatan ayahnya haruslah memiliki sertifikat dari sekolah tersebut.
Tidak hanya membuka sekolahnya sendiri dalam lingkungan keraton, Sultan juga memberikan subsidi dan bantuan keuangan untuk pendirian sekolah-sekolah yang banyak didirikan pada masa itu.
Sri Sultan Hamengku Buwono VII turun takhta pada tahun 1921 dan menunjuk putranya Gusti Raden Mas Sujadi sebagai pengganti.
Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921 – 1939)
Kondisi sosial yang stabil dan keuangan yang berlimpah membuat Kesultanan Yogyakarta leluasa mengembangkan diri. Seni budaya berkembang pesat, banyak tarian baru diciptakan. Bahkan keraton sering menyelenggarakan pementasan wayang orang selama tiga hari tiga malam.
Pada masa ini keraton tampak jauh lebih terbuka. Pintu benteng tidak pernah ditutup, bahkan beberapa plengkung (gerbang benteng) dibongkar agar lalu lintas lebih leluasa.
Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pun mengirim putra-putranya untuk meneruskan pendidikan ke Eropa. Kepada putra-putranya beliau berpesan untuk mempelajari dan memahami cara berpikir orang Eropa. Di antara mereka, terdapat BRM Dorodjatun yang bersekolah di Belanda. Ia kelak menjadi sultan berikutnya.
Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga memugar dan mendirikan bangunan-bangunan baru di keraton. Unsur-unsur Eropa tampak kentara pada bagian-bagian tertentu.
Sri Sultan Hamengku Buwono VIII wafat pada tahun 1939 setelah menunjuk putranya BRM Dorodjatun sebagai pengganti.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintah mulai tahun 1940. Pada masa inilah terjadi perubahan besar-besaran di seluruh dunia. Perang Dunia II yang meletus di Eropa memantik Perang Pasifik. Jepang melibatkan diri ke kancah peperangan dan merebut Hindia-Belanda.
Pemerintahan kolonial kemudian dipegang oleh balatentara Jepang. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memanfaatkan kondisi ini untuk menata dan memperbaharui tata pemerintahan kesultanan. Salah satu pembaharuan yang cukup fenomenal pada saat itu adalah penghapusan jabatan Pepatih Dalem dalam struktur pemerintah. Selama ini jabatan Pepatih Dalem yang juga harus tunduk pada pemerintah kolonial telah membuat Sultan tidak memiliki kendali penuh atas kerajaan. Untuk pertama kalinya sejarah Jawa mencatat seorang raja memegang langsung kekuasaan birokrasi kerajaan. Bahkan sejak saat itu Sultan berkantor di kompleks Kepatihan, suatu hal yang berlangsung hingga saat ini.
Pada tahun 1945, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kalah. Kekuasaan kolonial di Hindia-Belanda mengalami kekosongan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan sigap mengambil keputusan. Kesultanan Yogyakarta menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut memiliki implikasi bahwa Kesultanan Yogyakarta akan tunduk pada hukum dan peraturan yang dimiliki Republik Indonesia. Keputusan ini bukan saja merubah peraturan yang ada, namun juga mengubah dasar kerajaan. Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya bersifat monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional.
Sri Sultan Hamengku Buwono wafat IX pada tahun 1988. Beliau digantikan putranya Bendara Raden Mas Herjuno Darpito yang dilantik pada tahun 1989 dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta pertama yang tidak lagi menandatangani kontrak politik dengan pemerintah kolonial.
Tiap zaman memiliki masalah dan tantangannya sendiri. Sultan yang bertakhta, sultan-sultan sebelumnya, dan sultan-sultan setelahnya, dituntut untuk mampu membaca tanda-tanda zaman kemudian membuat kebijakan berdasar tanda-tanda tersebut.
Sikap dan keputusan para sultan dalam menghadapi masalah dan tantangan itulah yang telah membentuk Keraton Yogyakarta seperti yang dikenal saat ini. Pilihan beradaptasi dan keberanian mereka mengambil resiko membuahkan warisan-warisan yang hingga kini terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman moral bagi manusia-manusia Jawa di mana pun mereka berada.